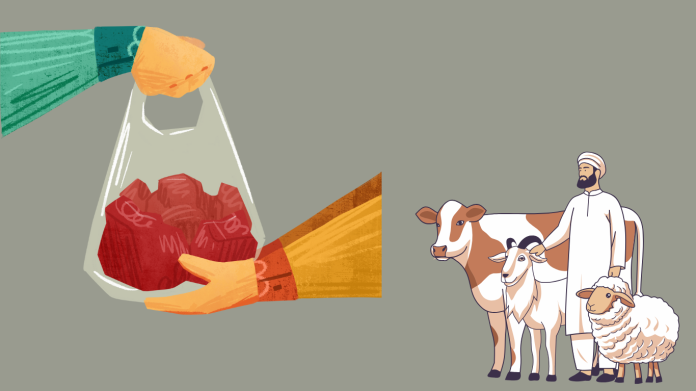Oleh: Dr. (HC) KH. Husein Muhammad
Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pembina Yayasan Fahmina, Pengasuh PP. Dar al Fiqr Arjawinangun
Seorang sahabat lama saya yang baik, Anick HT, mengirimkan kepada saya melalui WhatsApp sebuah tulisan dari seorang intelektual, penulis, sastrawan, spiritualis, dan kritikus terkemuka Indonesia, Denny JA. Judul tulisannya menarik perhatian: “Akan Menguatkah: Tafsir yang Tak Lagi Harus Hewan Dijadikan Kurban Ritus Agama?”
Denny tampaknya tengah merespons dengan antusias sebuah tulisan provokatif karya jurnalis Shahid Ali Muttaqi, berjudul “An Islamic Perspective Against Animal Sacrifice”. Inti pemikiran Muttaqi ialah harapan agar praktik kurban dalam ritual haji tidak harus selalu diwujudkan dalam bentuk penyembelihan hewan, tetapi bisa diganti dengan bentuk lain yang bernilai dan bermanfaat.
Saya membaca tulisan itu dengan penuh minat. Isu semacam ini sebenarnya telah lama ada dalam benak saya, dan selalu ingin saya diskusikan setiap kali Bulan Haji tiba, sebagaimana ketika kita membicarakan zakat. Maka, saya pun terdorong untuk menulis tanggapan ini. Semoga bermanfaat.
Makna dan Tujuan Qurban
Prosesi terakhir dalam pelaksanaan ibadah haji adalah penyembelihan hewan kurban. Ini sebenarnya merupakan ritual tambahan dan bersifat anjuran, kecuali bagi jamaah yang melanggar kewajiban haji, yang harus membayar denda. Dalam fikih, denda ini disebut “dam” yang secara harfiah berarti “darah”.
Kata qurban sendiri secara etimologis berarti “mendekat” atau “mendekatkan diri”, dalam hal ini kepada Allah, melalui penyembelihan hewan ternak. Dalam istilah lain disebut udh-hiyah, yakni penyembelihan hewan pada Hari Raya Idul Adha.
Tujuan utama dari ritual ini adalah mendekatkan diri kepada Allah, atau dalam istilah spiritual disebut “taqwa”. Al-Qur’an menyatakan:
لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ… وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ
“Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya… Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Hajj [22]: 36)
Saya ingin menekankan bahwa makna hakiki dari taqwa adalah pengendalian potensi kemanusiaan untuk mewujudkan kebaikan sosial dan menghindari keburukan sosial.
Transformasi Tradisi dan Kontekstualisasi Makna
Tradisi penyembelihan awalnya berasal dari masyarakat pagan. Para pemuka adat Arab pra-Islam, dengan mengatasnamakan Tuhan, bahkan sampai menyembelih anak manusia sebagai bentuk pengorbanan. Ini adalah praktik keagamaan yang secara akal dan etika merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Islam hadir untuk mengubah praktik ini, bukan dengan menghapus semangat pengorbanan, tetapi menggantinya dengan penyembelihan hewan, yang lebih manusiawi dan bermanfaat secara sosial.
Penafsir modern seperti Rasyid Ridha menyatakan bahwa ibadah kurban melambangkan perjuangan untuk mewujudkan kebenaran yang menuntut kesabaran, ketabahan, dan pengorbanan besar.
Kurban dalam Islam, karena itu, lebih dari sekadar ritual: ia adalah simbol solidaritas sosial dan komitmen untuk kesejahteraan bersama.
Hal ini ditegaskan dalam ayat lain:
وَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ…
“Maka apabila telah roboh (mati), makanlah sebagian darinya dan berilah makan kepada orang yang rela dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta…” (QS. Al-Hajj [22]: 36)
Ayat ini menegaskan bahwa aspek sosial dari kurban adalah memberi kepada yang membutuhkan. Islam berpihak pada mereka yang lemah secara ekonomi. Maka dari itu, menyembelih hewan mestinya diiringi dengan semangat menyembelih sifat kebinatangan dalam diri: egoisme, ketamakan, dan ketidakpedulian terhadap penderitaan sesama.
Dengan begitu, pemaknaan terhadap teks suci tidak harus terkungkung dalam pemahaman literal atau tekstual semata. Sebab, teks hadir dalam ruang dan waktu tertentu; ia lahir dari konteks sosial dan kultural yang spesifik.
Realitas sebagai Basis Penafsiran
Pemikir progresif asal Mesir, Dr. Nasr Hamid Abu Zaid, pernah mengatakan:
“Realitas adalah dasar yang tak bisa diabaikan. Dari realitas lahirlah teks, dan dari bahasa serta budaya teks terbentuk sistem maknanya. Pemaknaan akan terus berkembang seiring dengan gerak sosial. Mengabaikan realitas demi mempertahankan teks yang beku justru menjadikan teks itu legenda semata, karena kehilangan sisi kemanusiaannya.”
Kurban dalam Konteks Budaya
Islam lahir di Jazirah Arab, yang kala itu didominasi budaya nomaden. Suku-suku Badui menggantungkan hidupnya pada ternak: kambing, domba, dan unta—sebagai sumber makanan dan penghidupan.
Nabi Muhammad SAW sendiri semasa kecil menggembalakan kambing, dan dalam banyak perjalanan beliau menggunakan unta sebagai kendaraan. Maka, wajar bila kurban dalam bentuk hewan sangat relevan dalam konteks masyarakat Arab saat itu.
Namun, dunia kini telah berubah. Di Indonesia, misalnya, daging ayam dan ikan lebih akrab dengan kebutuhan pangan masyarakat dibanding unta atau domba. Maka, memberikan ayam atau ikan kepada mereka yang membutuhkan bisa menjadi bentuk lain dari semangat berkurban.
Seperti halnya zakat fitrah: Nabi menyebutkan kurma, gandum, atau syi’ir sebagai bentuk zakat, sesuai dengan makanan pokok saat itu. Di Indonesia, zakat fitrah dibayar dengan beras atau uang—karena itulah kebutuhan pokok yang relevan secara kontekstual.
Hukum yang Berubah Bersama Zaman
Perubahan hukum adalah keniscayaan dalam sejarah. Sebagaimana kaidah fikih menyatakan:
“Fatwa dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, niat, dan kebiasaan.” (Ibn Qayyim, I’lam al-Muwaqqi’in, jilid III, hlm. 3)
Ibn Qayyim juga menegaskan:
“Syariat Islam dibangun atas dasar kebijaksanaan dan kemaslahatan umat. Jika suatu hukum keluar dari keadilan, kasih sayang, dan maslahat, maka hukum itu bukanlah bagian dari syariat, meskipun diatasnamakan agama.”
Dalam al-Furuq, Imam Syihab al-Din al-Qarafi juga menyampaikan:
“Jika ada seseorang datang dari luar daerahmu meminta fatwa, jangan berikan berdasarkan kebiasaan daerahmu. Tanyakanlah adat istiadat di tempat asalnya, dan berikan fatwa berdasarkan itu. Membeku pada teks-teks lama adalah kekeliruan dalam memahami agama dan maksud para ulama.”
Penutup
Akhirnya, saya merasa penting untuk mendukung pandangan Shahid Ali Muttaqi, bahwa kurban tidak harus dalam bentuk hewan. Kurban bisa diwujudkan dalam bentuk apa pun yang bermanfaat bagi masyarakat, sesuai kebutuhan pokok dan tradisi setempat.
Inilah saatnya kita menafsir ulang makna kurban, dari sekadar penyembelihan hewan menjadi aksi nyata solidaritas sosial yang kontekstual dan bermakna. []