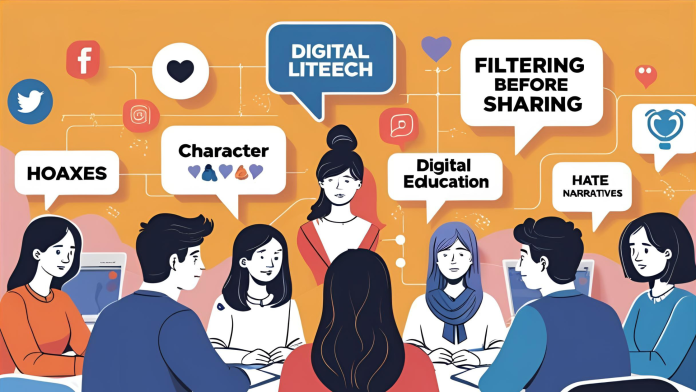Oleh: Muhammad Nashrul Abdillah
“Di balik setiap klik dan unggahan, ada nilai yang kita rawat, atau luka yang kita tinggalkan. Dunia digital tak hanya soal teknologi, tapi soal kemanusiaan yang sedang kita pertaruhkan.”
Era digital menuntut manusia untuk bergerak serba cepat. Tak hanya berkembang di negara-negara maju seperti Eropa, digitalisasi juga telah merambah dan mengakar kuat di Indonesia. Generasi muda kini tumbuh dalam lingkungan yang dikelilingi oleh layar. Gawai menjadi bagian dari keseharian mereka—bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas diri. Berjam-jam waktu dihabiskan untuk berselancar di media sosial, dunia semu yang menawarkan kemudahan sekaligus menyimpan ancaman: narasi kebencian yang kian membanjiri ruang digital.
Ujaran kebencian, hoaks, dan informasi yang memecah belah seolah menjadi konsumsi harian. Tanpa disadari, generasi kita mulai terpapar, bahkan ikut melanggengkan narasi-narasi negatif tersebut. Menurut laporan We Are Social tahun 2024, rata-rata waktu penggunaan layar (screen time) masyarakat Indonesia melebihi 7 jam per hari—lebih dari separuhnya dihabiskan di media sosial. Jika ruang digital terus dipenuhi konten negatif, generasi muda sangat berisiko terdampak, baik dari segi cara pandang, pembentukan karakter, hingga moralitas.
Lalu, mengapa generasi muda begitu rentan? Karena mereka berada pada fase pencarian jati diri. Mereka haus validasi, mencari identitas sosial, dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan digital yang membentuk opini publik. Di sinilah algoritma media sosial bekerja: menyuguhkan konten yang memicu emosi pengguna, mendorong interaksi, dan mempercepat viralitas—termasuk konten provokatif dan penuh kebencian.
Narasi kebencian tidak hanya menyasar isu politik, tetapi juga menyentuh ranah sensitif seperti ras, agama, gender, orientasi seksual, hingga pilihan hidup. Dalam konteks ini, generasi muda tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku dan penyebar. Nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan terancam terkikis.
Di titik ini, patut kita renungkan: di mana letak kegagalan sistem pendidikan dalam menanamkan filter moral terhadap konten digital? Riset Oktaviani berjudul Literasi Digital dalam Pendidikan Karakter Remaja menunjukkan bahwa banyak pelajar SMA di kota-kota besar belum mampu membedakan berita benar dan hoaks secara konsisten. Lebih mengkhawatirkan, sebagian dari mereka menganggap menghina kelompok lain sebagai bentuk bercanda yang wajar.
Literasi digital tak cukup berhenti pada aspek teknis. Ia harus menyentuh sisi etika dan emosional. Literasi bukan sekadar tahu cara mengoperasikan perangkat atau memfilter konten, tetapi juga mengajarkan bagaimana mengendalikan jari dan pikiran saat berselancar di dunia maya: dengan bijak, bertanggung jawab, kritis, dan berempati. Kita tak hanya butuh generasi yang cerdas pengetahuan, tapi juga cerdas dalam sikap dan rasa.
Prinsip “saring sebelum sharing” perlu dijadikan budaya, bukan sekadar slogan. Kebiasaan reflektif seperti berpikir sebelum membagikan konten memiliki dampak besar. Kita harus berhenti menormalisasi unggahan bernada hinaan atau stereotip, meskipun dikemas secara lucu. Sebab, setiap kata yang kita unggah dapat berdampak positif—menumbuhkan kemanusiaan—atau sebaliknya, melukai orang lain. Generasi muda harus sadar bahwa jejak digital bersifat abadi dan sulit dihapus.
Tanggung jawab memfilter konten negatif tidak bisa dibebankan pada individu semata. Ini adalah kerja kolektif yang melibatkan pemerintah, institusi pendidikan, keluarga, dan platform digital. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah program Siberkreasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang aktif mengadakan pelatihan literasi digital di berbagai daerah. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan kuat dari sekolah dan keluarga sebagai lingkar terdekat anak muda.
Sekolah memiliki peran besar dalam membentuk pola pikir yang inklusif dan toleran. Pendidikan karakter tidak boleh berhenti di tataran teori, tetapi harus diwujudkan dalam praktik sehari-hari—termasuk dalam interaksi digital. Di sisi lain, keluarga juga memegang peran penting dengan membangun ruang dialog yang sehat tentang dunia digital. Sayangnya, banyak orang tua yang memilih menjauh dari diskusi media sosial karena merasa itu di luar ranah mereka. Padahal, dari sinilah pembelajaran awal tentang etika bermedia bisa dimulai.
Platform digital sebagai rumah utama penyebaran informasi juga harus bertanggung jawab. Mereka memiliki kemampuan untuk menekan penyebaran ujaran kebencian melalui sistem deteksi otomatis, algoritma etis, dan kontrol komunitas yang ketat. Meta, Google, X (d/h Twitter) dan lainnya perlu lebih proaktif dalam menghapus akun provokatif, memberi peringatan, serta melabeli hoaks.
Namun, semua upaya itu akan sia-sia tanpa partisipasi aktif masyarakat. Di sinilah pentingnya muncul gerakan digital berbasis empati dan kemanusiaan. Kampanye seperti #BijakBermedia, #IndonesiaTanpaUjaranKebencian, dan #SaringSebelumSharing menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat bisa mengarahkan arus digital ke arah yang positif.
Pencegahan tak cukup hanya dalam bentuk teori, tetapi perlu tindakan nyata. Kita membutuhkan lebih banyak figur publik dan influencer yang menyebarkan pesan edukatif, bukan hanya sensasi. Kita juga perlu mendukung konten kreatif yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mencerdaskan serta memperkuat nilai kemanusiaan.
Teknologi akan terus berkembang. Gadget makin canggih, media sosial makin intens, dan kecerdasan buatan akan semakin personal. Namun, satu hal yang tak boleh kita tinggalkan adalah hati nurani. Dari sanalah nilai-nilai kemanusiaan lahir dan hidup.
Sudah saatnya kita memaknai ulang interaksi digital. Jadikan gadget sebagai alat pemersatu, bukan pemecah. Saring kebencian dengan pengetahuan, dan tumbuhkan empati melalui keberanian untuk berkata baik—meski dalam riuhnya dunia maya. Dari gadget ke hati, dari klik ke nurani—itulah perjalanan penting yang harus kita tempuh bersama demi menciptakan ruang digital yang sehat dan manusiawi.